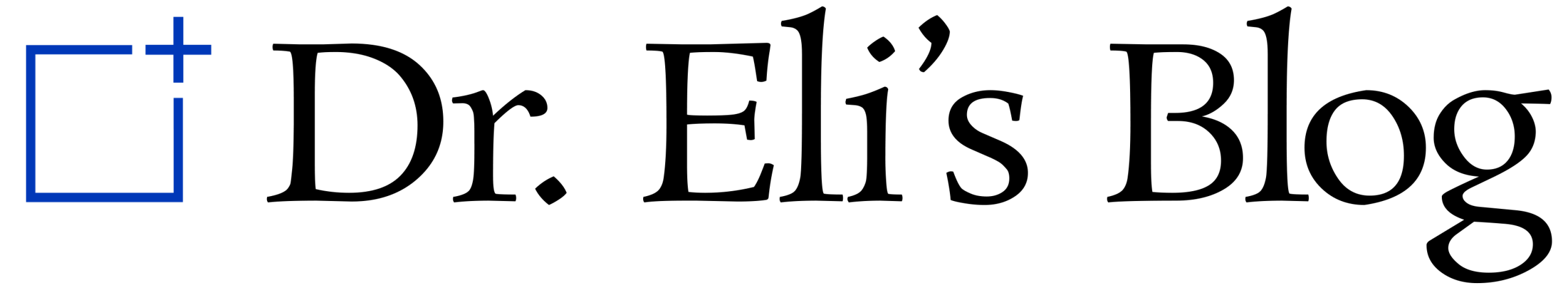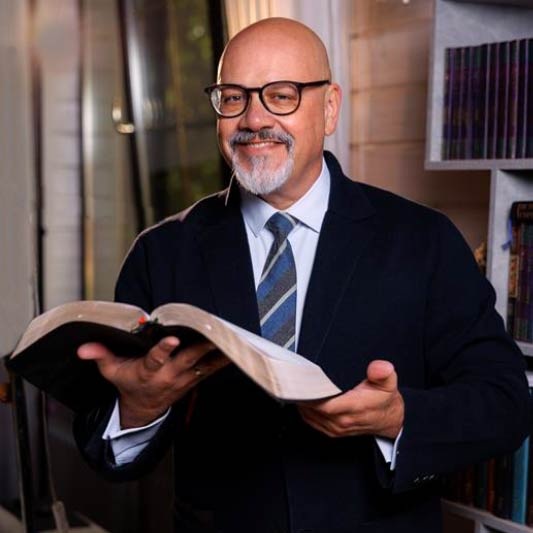Dalam bahasa modern, kata “kudus” sering dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat etis atau moral. Ungkapan seperti “lebih kudus darimu” memberi kesan seolah-olah orang yang dianggap kudus itu lebih benar secara moral dibanding orang lain. Tetapi, pemahaman modern ini sebenarnya sangat berbeda dari konsep kekudusan dalam Alkitab Ibrani kuno. Dalam Alkitab Ibrani, kata “kudus” (קדושׁ; qadosh) makna utamanya adalah “disendirikan – dikhususkan” atau “dipisahkan,” bukan berarti sempurna secara moral. Demikian juga, kata-kata yang berhubungan seperti “tahir” (טהור; tahor) dan “najis” (טמא; tame) sering dianggap hal-hal yang menyangkut moral di zaman modern, namun secara Alkitabiah pengertian kata-kata itu lebih berkaitan dengan kemurnian dalam ritual dan pemisahan, bukan soal dosa atau keselamatan. Melalui konsep-konsep ini, para penulis Kitab Suci bangsa Israel merancang batasan-batasan yang membentuk hubungan unik antara Allah dan manusia, dan menekankan keunikan, bukan keunggulan secara etika.
Panggilan untuk hidup kudus adalah inti dari hukum Taurat. Dalam Imamat 19:2 (TB), Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel melalui Musa: “Kuduslah kamu (קדושׁים; qedoshim), sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus (קדושׁ; qadosh).” Sekilas, perintah ini terdengar seperti Allah sedang menuntut agar bangsa Israel meniru kesempurnaan moral-Nya. Tetapi jika kita melihat konteks yang lebih luas dalam hukum Taurat, maknanya tidaklah demikian tetapi sebaliknya. Tepat sebelum perintah ini diberikan, Imamat 16:21 (TB) menjelaskan sistem pengorbanan yang Allah tetapkan untuk menghapus “segala kesalahan bangsa Israel.” Sistem ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui ketidak sempurnaan manusia dan menyediakan cara untuk mengatasi pelanggaran mereka. Jadi, kekudusan tidak dapat diartikan tanpa dosa atau moral tanpa cela, karena Allah sudah mengantisipasi kegagalan bangsa Israel. Dengan demikian, menjadi kudus berarti menjadi umat yang “dipisahkan” dari bangsa-bangsa lain, berbeda dalam identitas dan tujuan hidup.
Ayat-ayat sesudah perintah Allah untuk menjadi kudus menjelaskan bagaimana pemisahan ini dijalankan. Imamat 19:3-4 (TB) memerintahkan, “Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabat-Ku; Akulah TUHAN, Allahmu.” dan “Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan; Akulah TUHAN, Allahmu.” Perintah ini menunjukkan tradisi yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Tidak seperti bangsa lain, bangsa Israel menjaga hari Sabat—sebuah hari yang telah dikhususkan sebagai hari kudus sejak awal penciptaan, ketika “Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya (קדושׁ)” (Kejadian 2:3 (TB)). Dengan menjauhi penyembahan berhala—praktik umum di antara bangsa-bangsa lain—bangsa Israel semakin menunjukkan jati dirinya sebagai umat yang berbeda. Menjaga Sabat dan menyembah satu Allah bukanlah tanda bahwa mereka lebih unggul secara moral, melainkan perwujudan dari hubungan perjanjian yang unik dengan Allah, yang memisahkan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, milik Allah sepenuhnya.
Kekudusan Allah Israel menegaskan kembali ide tentang pemisahan ini. Saat Allah menyatakan, “Aku, TUHAN, Allahmu, kudus” (Imamat 19:2 (TB)), ayat ini bukan sekadar menyatakan sifat moral Allah, tetapi menegaskan keunikan Allah yang berbeda dari semua dewa lain. Hal ini terlihat jelas dalam perintah pertama dari Sepuluh Perintah Allah, atau “Sepuluh Firman” (עשרת הדברים; aseret hadevarim; Keluaran 34:28 (TB)), yang berbunyi, “Jangan ada padamu allah lain (אלהים; elohim) di hadapan-Ku” (Keluaran 20:3 (TB)). Dalam bahasa Ibrani, frasa ini secara harfiah berarti “di depan wajah-Ku” (על-פני; al-panai), artinya bangsa Israel tidak boleh menyembah dewa-dewa lain bersamaan dengan Tuhan. Bertentangan dengan pandangan modern yang mungkin berpikir bahwa dewa-dewa lain itu tidak ada, namun dalam pandangan dunia kuno, perintah ini mengakui keberadaan dewa-dewa lain. Allah Israel itu kudus—dipisahkan—karena Dia menuntut pengabdian total, membedakan diri-Nya dari semua dewa-dewa bangsa lain. Kekudusan bangsa Israel mencerminkan perbedaan Allah ini— berakar dari kesetiaan kepada satu Allah saja, bukan karena moral yang sempurna.
Pemahaman tentang kekudusan ini membantah pandangan modern yang salah konsep yakni menyamakan kekudusan dengan kebenaran moral. Dalam Ulangan 7:6 (TB), bangsa Israel disebut sebagai “umat yang kudus (קדושׁ) bagi TUHAN,” tetapi pada beberapa pasal kemudian, Musa memperingatkan agar mereka tidak merasa lebih bermoral. Dalam Ulangan 9:4-5 (TB) Ia berkata, “Janganlah engkau berkata dalam hatimu… karena kebenaran hatimu (צדקה; tsedakah), engkau masuk menduduki negeri mereka.” Sebaliknya, itu “karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu”—bukan karena kebenaranmu atau ketulusan (ישׁר; yosher) hatimu. Kekudusan bangsa Israel berasal dari pilihan Allah, bukan karena keunggulan moral. Jadi, istilah “kudus” tidak mengandung kesombongan spiritual seperti “lebih suci dari kamu” yang umum dalam budaya modern, melainkan bermakna dipisahkan untuk tujuan Allah semata, bukan keunggulan secara etika moral.
Konotasi kata “tahir” dan “najis” dalam Alkitab juga berbicara tentang pemisahan daripada soal moral. Dalam hukum Taurat, orang yang “najis” (טמא; tame) adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak layak untuk melakukan ritual ibadah, bukan berarti dia melanggar moral. Misalnya, dalam Imamat 13:11 (TB), seorang imam akan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki penyakit kusta adalah “najis” (טמא). Ini menggambarkan keadaan bahwa orang itu untuk sementara waktu tidak layak untuk ibadah, bukan penghakiman terhadap karakter orang tersebut. Ketika ia sudah sembuh, orang itu bisa menjalani pemeriksaan oleh imam, lalu “mencuci pakaiannya dan menjadi tahir (טהר; taher)” (Imamat 13:6 (TB)). Dalam hal ini, menjadi tahir berarti kembali dalam kondisi bersih (kudus) untuk ritual, bukan penghapusan dosa. Dalam kitab Imamat, juga ditegaskan dengan menggunakan kata “tahir” (טהורה; tehorah) untuk menggambarkan minyak murni untuk lampu di Kemah Suci (Imamat 24:2 (TB)), yang memperjelas bahwa “tahir” berhubungan dengan kelayakan lahiriah untuk ritual ibadah, bukan kondisi moral secara batin.
Keterkaitan antara kata “kudus,” “tahir,” dan “najis” semakin terlihat jelas penekanannya semuanya berbicara tentang pemisahan. Imamat 10:10 (TB) Allah memerintah Harun, “Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus (קדושׁ) dengan yang tidak kudus (biasa) (חל; hol), antara yang najis (טמא) dan yang tidak najis (tahir) (טהור).” Ayat ini menyandingkan kekudusan dengan tidak najis (tahir), dan tidak kudus (biasa) dengan najis, menunjukkan konsep yang tumpang tindih. Sama seperti yang kudus dipisahkan dari yang biasa, yang tahir dipisahkan dari yang najis. Baik kekudusan maupun tahir bukan berarti lebih baik secara moral; keduanya menunjukkan keadaan yang berbeda yang memungkinkan seseorang bisa ikut serta dalam ruang dan ibadah yang kudus. Misalnya, para imam dan umat yang ingin mendekat kepada Allah harus melalui ritual pembersihan supaya tahir, untuk memastikan kekudusan pertemuan antara Allah dengan manusia.
Penekanan Alkitab terhadap pemisahan ini merefleksikan tujuan yang lebih besar yaitu membangun ikatan yang erat antara Allah dengan bangsa Israel. Kekudusan dan kemurnian ritual bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan cara untuk menjaga hubungan perjanjian itu. Dengan memelihara hari Sabat, menolak penyembahan berhala, dan mengikuti hukum kekudusan, bangsa Israel menunjukkan identitasnya sebagai umat pilihan Allah, dipisahkan untuk melayani Allah. Praktik-praktik ini menciptakan sarana yang memungkinkan kehadiran Allah tinggal di tengah umat-Nya, sebagaimana dilambangkan oleh keberadaan Kemah Suci dan kemudian Bait Allah. Kategori seperti kudus, tahir, dan najis menjadi batas-batas yang melindungi dan membentuk hubungan yang kudus ini—bukan sebagai ukuran nilai moral.
Bagi pembaca masa kini, memahami arti kata “kudus,” “tahir,” dan “najis” dalam bahasa Ibrani bisa mengubah cara kita menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Kekudusan janganlah dianggap sebagai panggilan untuk menjadi sempurna secara moral, tetapi kita harus memahaminya sebagai ajakan untuk hidup dengan cara yang berbeda dalam kesetiaan kepada Allah, sama seperti bangsa Israel yang dipanggil untuk menjadi umat yang dipisahkan melalui tata cara ibadahnya. Demikian juga, konsep tahir dan najis mengingatkan kita bahwa pandangan bangsa Israel kuno selalu mengutamakan kesiapan ritual daripada penilaian etis dalam hal penyembahan. Pemahaman ini membantah kecenderungan modern yang sering menerjemahkan istilah-istilah Alkitab secara moral dan membantu kita menghargai konteks budaya dan teologis dari Kitab Suci Ibrani dengan lebih mendalam.
Kesimpulan, pengertian kekudusan menurut Alkitab, sebagaimana dinyatakan melalui istilah Ibrani קדושׁ (qadosh), berfokus pada pemisahan demi mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah, bukan untuk mendapatkan keunggulan dalam moral. Demikian juga, “tahir” (טהור; tahor) dan “najis” (טמא; tame) menggambarkan kondisi kemurnian untuk ritual, bukan status moral seseorang. Melalui konsep-konsep ini, Taurat memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk memelihara hubungan yang unik dengan Allah yang kudus, berbeda dari bangsa-bangsa lain dan dewa-dewa mereka. Dengan kembali pada pemahaman asli ini, kita dapat melepaskan diri dari kesalahpahaman zaman modern dan terhubung kembali dengan pandangan Alkitab kuno tentang sebuah bangsa yang dipanggil untuk menjadi kudus—dipisahkan, dikhususkan, dan terikat kepada TUHAN Allah mereka.