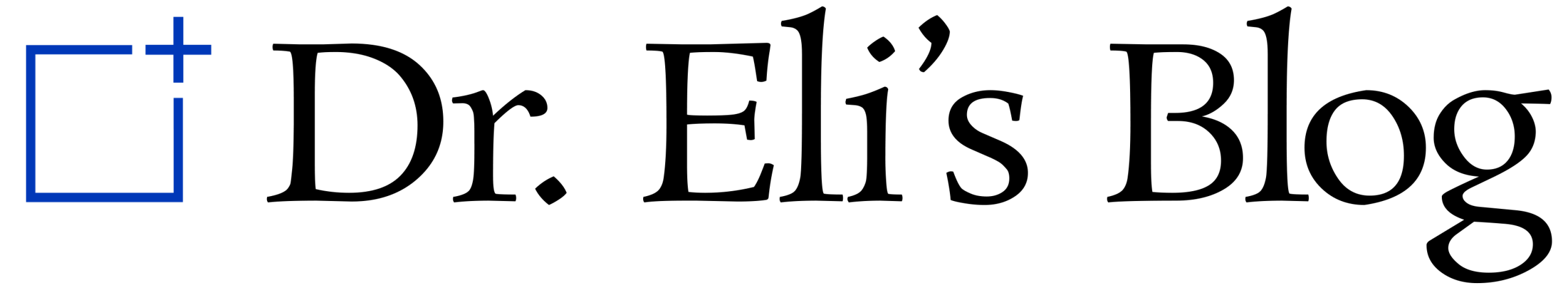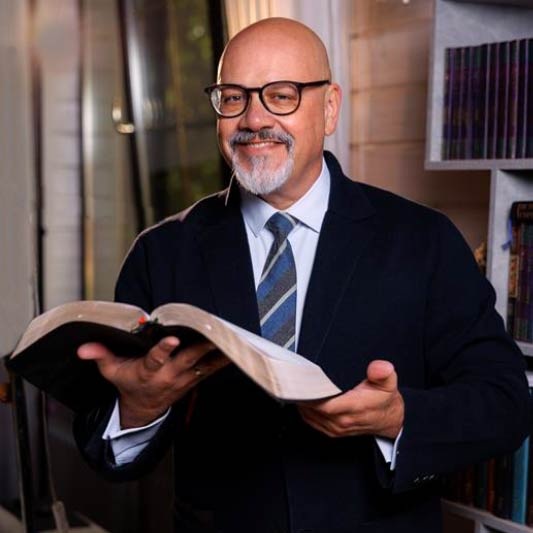Sebutan bagi Maria sebagai “Ratu Surga” atau “Ibu Suri yang Baru” dalam teologi Katolik bersumber dari tradisi Alkitab dan sejarah yang kaya, yang memberikan peran yang unik bagi para ibu dari raja-raja Yehuda dalam Alkitab Ibrani. Konsep ini, yang berakar dari istilah dalam Perjanjian Lama gebira (גְּבִירָה)—sering diterjemahkan sebagai “nyonya” atau “Ibu Suri”—menunjukkan bahwa ibu dari seorang raja memiliki kedudukan resmi yang penting di istana kerajaan, menempati posisi kedua setelah sang raja sendiri. Para teolog Katolik berpendapat bahwa jika Yesus adalah Raja Daud yang tertinggi, maka Maria, ibu-Nya, memiliki peran sebagai gebira yang tertinggi—ibu suri dalam Kerajaan Allah. Namun, tafsiran ini tidak lepas dari perdebatan akademis, sebab bukti mengenai peran gebira masih dipertentangkan. Artikel ini membahas penggambaran ibu-ibu dari raja Yehuda dalam Alkitab, konsep gebira, argumen bahwa Maria adalah Ibu Suri yang Baru, serta tantangan-tantangan kritis terhadap identifikasi ini, sambil menilai implikasi teologis dan ekumenisnya.
Ibu Raja-Raja Yehuda di dalam Alkitab Ibrani
Kitab 1 dan 2 Raja-Raja mencatat nama hampir semua ibu dari raja-raja Yehuda secara teliti, sebuah kebiasaan yang menegaskan pentingnya peran mereka dalam kerajaan Daud. Misalnya, 1 Raja-Raja 14:21 mencatat bahwa ibu Rehabeam adalah Naama, seorang perempuan Amon; 1 Raja-Raja 15:1–2 menyebut ibu Abiam adalah Maakha; dan 2 Raja-Raja 8:25–26 menuliskan bahwa ibu Ahazia adalah Atalya. Dari sembilan belas Ibu Suri yang disebut, hanya ibu Yoram dan Ahas yang tidak dicantumkan (2 Raja-Raja 8:16; 16:1). Penyebutan nama ibu suri yang konsisten ini mengindikasikan peran mereka lebih dari sekadar hubungan biologis, mengisyaratkan posisi pengaruh atau otoritas di istana Yudea.
Beberapa contoh yang spesifik menunjukkan kedudukan istimewa itu. Batsyeba, ibu dari Salomo, merupakan tokoh penting dalam masa kerajaan yang bersatu. Dalam 1 Raja-Raja 1:11–31, ia memainkan peran penting ketika membuat Salomo naik takhta, dan dalam 1 Raja-Raja 2:13–25, ketika ia datang memohon mewakili Adonia, Salomo bangkit dari singgasananya, tunduk menyembah kepadanya, dan mempersilakannya duduk di sebelah kanannya—sebuah sikap penuh hormat dan pengakuan otoritas. Maakha, ibu Asa, memiliki pengaruh religius yang kuat; terlihat ketika ia membuat patung Dewi Asyera, ia dilengserkan dari posisinya sebagai gebira (1 Raja-Raja 15:13). Atalya, ibu Ahazia, merebut takhta dan memerintah selama enam tahun setelah kematian putranya (2 Raja-Raja 11), hal ini memperlihatkan kekuasaan politiknya yang besar. Nehusta, ibu Yoyakhin, disebutkan secara khusus dalam kisah pembuangan (2 Raja-Raja 24:15), sementara Hamutal, ibu Yoahas dan Zedekia, menegaskan peran penting yang terjadi berulang-ulang dari para ibu suri (2 Raja-Raja 23:31). Bahkan Izebel, ratu dari kerajaan utara, mendapat penghormatan dari para utusan Yehuda (2 Raja-Raja 10:13), menunjukkan kekuasaannya.
Semua contoh ini menunjukkan bahwa ibu seorang raja memiliki peran tersendiri—baik dalam bidang politik, keagamaan, maupun perantaraan. Penyebutan nama wanita-wanita ini secara konsisten dalam Alkitab, beserta catatan dari tindakan mereka, mendukung gagasan bahwa mereka bukan tokoh yang hanya numpang lewat, melainkan menjadi bagian integral dari pemerintahan dan warisan dinasti Daud.
Konsep Gebira
Istilah Ibrani gebira (גְּבִירָה), yang sering diterjemahkan sebagai “wanita agung”, “nyonya”, atau “ratu”, muncul sebanyak lima belas kali dalam Alkitab Ibrani (misalnya Kejadian 16:4, 1 Raja-Raja 15:13, Yeremia 13:18). Dalam konteks kerajaan Yehuda, istilah ini kerap dikaitkan dengan ibu suri, sehingga menunjukkan jabatan atau peran resmi. Sarjana seperti Niels-Erik Andreasen berpendapat bahwa gebira memegang posisi politik yang penting— posisi kedua setelah raja—dengan akses langsung dan pengaruh besar terhadap sang raja. Interaksi Batsyeba dengan Salomo, otoritas religius Maakha, perebutan takhta oleh Atalya, dan peran Nehusta dalam masa pembuangan semuanya mendukung pandangan ini. Gebira sering bertindak sebagai penasihat, perantara, atau tokoh religius yang mewakili kepentingan istana dan rakyat.
Namun, interpretasi ini tidak diterima secara universal. Sarjana Israel Zafira Ben-Barak menentang pandangan bahwa gebira merupakan jabatan formal, dengan alasan bahwa bukti yang ada terlalu sedikit dan tidak konsisten untuk mendukung sebuah teori secara menyeluruh. Ia mencatat bahwa hanya ada empat ibu suri—Batsyeba, Maakha, Hamutal, dan Nehusta—yang mendapat perhatian yang mendalam dalam teks Alkitab, dan tindakan mereka bisa jadi merupakan pengecualian, bukan pola umum. Menurut Ben-Barak, kesimpulan yang luas tentang peran kelembagaan gebira terlalu dini, mengingat jumlah kasus yang terbatas dan tidak adanya bukti eksplisit tentang jabatan resmi yang konsisten di seluruh masa pemerintahan Yehuda.
Maria sebagai Ibu Suri yang Baru
Teologi Katolik menempatkan Maria, sebagai ibu Yesus—Raja Daud yang maha tinggi—menjadi gebira tertinggi, atau ibu suri, dalam Kerajaan Allah. Argumen ini didasarkan pada preseden Alkitabiah para ibu suri Yehuda, yang pengaruh dan kedudukannya menubuatkan posisi luhur Maria. Kekuasaan Yesus sebagai Raja berakar pada perjanjian Daud, sebagaimana tercatat dalam Lukas 1:32–33, dimana malaikat Gabriel menyatakan bahwa Yesus akan menerima “takhta Daud, bapa-Nya” dan “Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.” Jika para ibu dari kerajaan Daud memiliki kedudukan istimewa, maka secara logika : Maria, ibu Sang Raja kekal, juga menerima status yang serupa—bahkan lebih tinggi.
Gambaran dalam Wahyu 12:1–2, yang melukiskan seorang perempuan “berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya,” memperkuat pandangan ini. Simbol langit dan mahkota menggambarkan sosok ratu, dan perannya sebagai ibu Sang Mesias (Wahyu 12:5) selaras dengan identitas Maria dalam Injil. Rujukan kepada “anak-anaknya yang lain” (Wahyu 12:17), yang berpegang pada kesaksian Yesus, mendukung penafsiran Katolik bahwa Maria adalah ibu rohani Gereja—peran yang digambarkan sebelumnya oleh gebira sebagai sosok pengantara dan pelindung umat. Dalam Yohanes 19:26–27, Yesus mempercayakan Maria kepada murid yang dikasihi-Nya, menjadikannya ibu bagi orang percaya, sejajar dengan peran gebira sebagai figur ibu dalam kerajaan.
Tradisi Katolik, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lumen Gentium (1964), menekankan bahwa status ratu dari Maria merupakan perpanjangan dari statusnya sebagai Ibu Ilahi. Perannya sebagai pengantara, seperti yang terlihat dalam peristiwa Perkawinan di Kana (Yohanes 2:1–11), mencerminkan fungsi gebira sebagai pembela, sebagaimana Batsyeba mengajukan permohonan kepada Salomo. Penghormatan yang terus-menerus kepada Maria sebagai Ratu Surga dalam tradisi Katolik dan Ortodoks mencerminkan kerangka teologis ini—yang berakar dari penggambaran Alkitab tentang para ibu suri Yehuda.
Penilaian Kritis
Meskipun argumen yang menempatkan Maria sebagai Ibu Suri yang Baru (New Queen Mother) cukup meyakinkan, pandangan ini menghadapi sejumlah pertentangan. Pertama, tidak terdapat bukti Alkitab yang kuat tentang gebira sebagai jabatan formal. Walaupun Ibu Suri sering disebut serta pengaruh mereka yang dicatat menunjukkan bahwa peran mereka penting, para ahli seperti Ben-Barak menyoroti kurangnya bukti yang konsisten di seluruh masa pemerintahan. Tindakan Batsyeba, Maakha, dan Atalya mungkin bersifat pengecualian, bukan secara umum, dan istilah gebira sendiri tidak selalu secara eksplisit mengacu pada ibu suri dalam Alkitab Ibrani (misalnya, Yesaya 47:5 memakai istilah gebira untuk Babel). Ketidakjelasan ini melemahkan argumen bahwa setiap ibu raja Yehuda memiliki posisi resmi yang standard.
Kedua, Perjanjian Baru tidak secara eksplisit menyebut Maria sebagai ibu suri atau gebira. Meskipun Lukas 1:32–33 menegaskan bahwa Yesus adalah Raja keturunan Daud, dan Wahyu 12 menggambarkan sosok yang tampak seperti ratu, hubungannya dengan Maria hanya berdasarkan tafsir teologis saja, bukan bukti tekstual yang eksplisit. Gambaran dalam Wahyu 12 kemungkinan besar melambangkan Israel atau Gereja, namun ada kemungkinan Maria atau bisa jadi keduanya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Yohanes 19:26–27 memang mendukung konsep Maria sebagai ibu rohani, tetapi tidak secara explisit memberinya gelar ratu. Oleh karena itu, argumen Katolik bergantung pada sintesis tipologi Alkitab dan tradisi gereja kemudian, yang mungkin kurang meyakinkan bagi mereka yang menekankan pada dasar Alkitab secara eksplisit.
Ketiga, konteks historis dan budaya tentang gebira juga perlu diperhatikan. Peran ibu suri di Yudea tampaknya mencerminkan praktik di Timur Dekat kuno, di mana ibu raja memiliki pengaruh karena kedekatannya dengan kekuasaan dan perannya dalam menjamin suksesi kerajaan. Namun, menerapkan pandangan ini kepada Maria memerlukan jembatan konseptual antara konteks Yudea abad pertama dengan kerajaan Allah yang kekal—sebuah lompatan yang menghubungkan kerajaan duniawi dengan Kerajaan Allah. Para sarjana Protestan, yang berhati-hati agar tidak meninggikan Maria melampaui kesaksian Alkitab, melihat hal ini berlebihan dan lebih memilih penafsiran yang menekankan otoritas tunggal Yesus.
Implikasi untuk Dialog Teologis
Mempertanyakan Maria sebagai Ibu Suri yang Baru menimbulkan ketegangan yang lebih dalam antara hermeneutik Katolik dan Protestan. Teologi Katolik, yang menekankan tradisi dan tipologi, memandang ke-ratu-an Maria sebagai kelanjutan dari perannya sebagai ibu Raja keturunan Daud, didukung dengan pandangan gebira dan gambaran dalam kitab Wahyu. Sementara itu, tradisi Protestan menekankan sola scriptura (hanya berdasarkan Kitab Suci), sering menolak penafsiran semacam ini karena tidak adanya pernyataan eksplisit yang sah dalam Perjanjian Baru. Pandangan hibrid terhadap Wahyu 12—yang melihat perempuan itu sebagai Maria dan sekaligus Israel/Gereja—dapat menjadi jembatan yang potensial, karena mengakui peran unik Maria sekaligus menempatkannya dalam komunitas perjanjian yang lebih luas.
Perdebatan tentang peran gebira juga membuka ruang refleksi ekumenis. Mengakui pentingnya tokoh ibu suri dalam Alkitab dapat membantu kaum Protestan memahami bahwa penghormatan Katolik terhadap Maria berakar dalam konteks Yudaisme, bukan perkembangan dogma baru. Sebaliknya, pihak Katolik juga harus mempertimbangkan kritik akademis terhadap peran gebira untuk memperbaiki argumen mereka, memastikan bahwa pandangan mereka harus berdasarkan bukti tekstual yang kuat. Dialog semacam ini menumbuhkan rasa saling menghargai, mendorong umat Kristen untuk melihat pentingnya Maria melalui kacamata warisan Alkitab yang sama.
Kesimpulan
Identifikasi Maria sebagai Ibu Suri yang Baru merupakan penafsiran yang masuk akal dan kaya secara teologis, berakar pada gambaran Alkitab tentang gebira dan pada kerajaan Daud yang digenapi dalam diri Yesus. Penyebutan ibu suri Yehuda yang konsisten, catatan tentang pengaruh mereka, serta simbolisme dalam Wahyu 12 mendukung pandangan Katolik bahwa Maria memiliki peran istimewa sebagai figur ratu dalam kerajaan Allah. Namun, perdebatan akademis mengenai status kelembagaan gebira dan tidak adanya referensi eksplisit dalam Perjanjian Baru tentang Maria sebagai ibu suri mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap klaim yang terlalu dogmatis. Bukti-bukti yang ada bersifat tafsiran, bukan kepastian—mengundang orang percaya untuk terus menjelajahi kaitan antara tipologi Perjanjian Lama dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Penelitian semacam ini tidak saja memperdalam pemahaman kita akan peran Maria, tetapi juga mendorong komunitas Katolik dan Protestan untuk terlibat dalam dialog yang membangun, menghargai akar iman yang sama, sekaligus menghormati perbedaan penafsiran yang ada.